bismillah
Selama 6 semester saya belajar di ruang kelas Gedung K Fakultas Psikologi UGM, baru semester ini saya menyadari betapa psikologi adalah ilmu yang sangat cantik. Menyadur kalimat Mbak Setiawati Intan Savitri a.k.a Izzatul Jannah, sang novelis terkemuka di Indonesia, dalam kalimat pembuka tesisnya "Belum Cinta tetapi Menikah: Dinamika Perjodohan dalam Perkawinan Aktivis Pergerakan Islam" :
Itu baru emosi saja. Belum kita melirik pada bahasan yang lebih ekstrim, misalnya autisme. Saya memiliki adik bimbingan belajar di Sanggar Belajar Inklusif. Well, okay. Bukan adik bimbingan resmi sih, ya, karena saya mengajar secara suka rela di sana, tidak resmi. Jadi anggap saja 'seseorang yang saya anggap sbg adik'. Nama samarannya adalah Adi. Dia seorang autis. Usianya kira-kira 12 tahun, badannya tambun dan lucu. Setiap kali dia ditanya "Adi sudah mandi?" maka dia akan menjawab "Sudah, Bu." Kemudian jika ditanya lagi "Adi belum mandi?" maka dia akan menjawab "Belum, Bu."
See? Adi belum memahami makna kata. Dia baru menghafalnya. Jika ditanya 'sudah' maka dijawab 'sudah'. Jika pertanyaan diubah menjadi 'belum' maka dijawab 'belum'. Bukankah kita semua, we all human-being, need to understand words? Dan helloooo... Adi seorang autis, lho! Bagaimana memahamkannya terhadap makna kata? Anyone? Perasaan saya selalu bercampur aduk tiap kali melihat Adi. Senang, melihatnya tidak antisosial, mau belajar bersama teman-teman lainnya. Miris, kadang hopeless juga memikirkan bagaimana membuatnya paham terhadap sesuatu. Sebagaimana Bu Sullivan bingung terhadap Hellen Keller mungkin, ya. Yang jadi Bu Sullivan tentu bukan saya, tapi Bu Ammy, pembina Sanggar Belajar Inklusif. Bagaimana pula perasaan orang tua Adi? Wah, saya baru sadar kalau kontribusi saya di bidang pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus masih 0 besar, bahkan minus. I could do nothing :(
But hey! Bukankah Allah menciptakan segala sesuatu tidak dalam kerangka kesia-siaan? Kepercayaan ini yang selalu saya tumbuhkan dalam hati bahwa setiap anak di dunia ini, baik yang autis maupun ADHD ataupun yang lain, pasti Allah telah melekatkan kemanfaatan dalam diri mereka. Cepat besar ya, Nak. Semoga manfaatmu segera merekah dan mendunia... terima kasih telah menjadi 'guru' bagi kami... :')
Back to the topic. Belajar psikologi, belajar tentang manusia, human-being, objek yang subjektif, maka memang seharusnya kita lebih bijaksana dalam memaknai kehidupan, baik hidup kita maupun orang lain. Saya pun teringat akan 'kendaraan'-nya Ummar ibnu Al-Khattab, sabar dan syukur. Bukankah seharusnya, para pembelajar psikologi juga memiliki dua 'kendaraan' itu? Jika belum, semoga 2 contoh yang saya jabarkan di atas dapat sedikit membuka mata hati kita.
Allahu a'lam bish-showab.
P.S.:
emphaty is different with pity.
Selama 6 semester saya belajar di ruang kelas Gedung K Fakultas Psikologi UGM, baru semester ini saya menyadari betapa psikologi adalah ilmu yang sangat cantik. Menyadur kalimat Mbak Setiawati Intan Savitri a.k.a Izzatul Jannah, sang novelis terkemuka di Indonesia, dalam kalimat pembuka tesisnya "Belum Cinta tetapi Menikah: Dinamika Perjodohan dalam Perkawinan Aktivis Pergerakan Islam" :
Mempelajari psikologi, seharusnya membuat hidup lebih gemulai.Saya sangat setuju terhadapnya. Mempelajari psikologi emosi, misalnya. Pernahkah terpikir begitu signifikannya peran emosi dalam hidup seseorang? Bagaimana jika kompetensi emosi seseorang terdistorsi? Pascaoperasi otak, bisa jadi. Ada seorang ayah yang tinggal di UK (as far as I could remember... or USA. whatever. he lives on earth.) yang mengidap penggumpalan pembuluh darah otak sehingga harus dioperasi. Efek samping dari tindakan medis tersebut ternyata membuatnya tidak dapat mengenali wajah. Dia tahu wajah yang dilihatnya, namun tidak dapat memberikan label emosi terhadapnya. Tentu saja emosi tidak hanya terbatas pada emosi marah dan jijik namun juga emosi bahagia dsb. Dapatkah kita berempati terhadapnya, as if we were him? Setiap kali dia melihat anak-anaknya, dia tahu wajah-wajah itu namun tidak ada afek yang timbul dalam perasaannya. In another short sentence: dia tidak mengenali anak-anaknya. Dia tahu dan merasa pernah melihat wajah-wajah itu, namun tidak mengenal siapa pemilik wajah itu dan apa hubungannya dengan diri sang ayah.
Itu baru emosi saja. Belum kita melirik pada bahasan yang lebih ekstrim, misalnya autisme. Saya memiliki adik bimbingan belajar di Sanggar Belajar Inklusif. Well, okay. Bukan adik bimbingan resmi sih, ya, karena saya mengajar secara suka rela di sana, tidak resmi. Jadi anggap saja 'seseorang yang saya anggap sbg adik'. Nama samarannya adalah Adi. Dia seorang autis. Usianya kira-kira 12 tahun, badannya tambun dan lucu. Setiap kali dia ditanya "Adi sudah mandi?" maka dia akan menjawab "Sudah, Bu." Kemudian jika ditanya lagi "Adi belum mandi?" maka dia akan menjawab "Belum, Bu."
See? Adi belum memahami makna kata. Dia baru menghafalnya. Jika ditanya 'sudah' maka dijawab 'sudah'. Jika pertanyaan diubah menjadi 'belum' maka dijawab 'belum'. Bukankah kita semua, we all human-being, need to understand words? Dan helloooo... Adi seorang autis, lho! Bagaimana memahamkannya terhadap makna kata? Anyone? Perasaan saya selalu bercampur aduk tiap kali melihat Adi. Senang, melihatnya tidak antisosial, mau belajar bersama teman-teman lainnya. Miris, kadang hopeless juga memikirkan bagaimana membuatnya paham terhadap sesuatu. Sebagaimana Bu Sullivan bingung terhadap Hellen Keller mungkin, ya. Yang jadi Bu Sullivan tentu bukan saya, tapi Bu Ammy, pembina Sanggar Belajar Inklusif. Bagaimana pula perasaan orang tua Adi? Wah, saya baru sadar kalau kontribusi saya di bidang pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus masih 0 besar, bahkan minus. I could do nothing :(
But hey! Bukankah Allah menciptakan segala sesuatu tidak dalam kerangka kesia-siaan? Kepercayaan ini yang selalu saya tumbuhkan dalam hati bahwa setiap anak di dunia ini, baik yang autis maupun ADHD ataupun yang lain, pasti Allah telah melekatkan kemanfaatan dalam diri mereka. Cepat besar ya, Nak. Semoga manfaatmu segera merekah dan mendunia... terima kasih telah menjadi 'guru' bagi kami... :')
Back to the topic. Belajar psikologi, belajar tentang manusia, human-being, objek yang subjektif, maka memang seharusnya kita lebih bijaksana dalam memaknai kehidupan, baik hidup kita maupun orang lain. Saya pun teringat akan 'kendaraan'-nya Ummar ibnu Al-Khattab, sabar dan syukur. Bukankah seharusnya, para pembelajar psikologi juga memiliki dua 'kendaraan' itu? Jika belum, semoga 2 contoh yang saya jabarkan di atas dapat sedikit membuka mata hati kita.
Allahu a'lam bish-showab.
P.S.:
emphaty is different with pity.
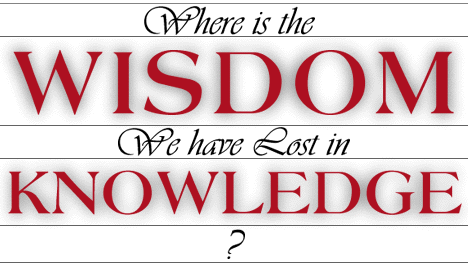
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar